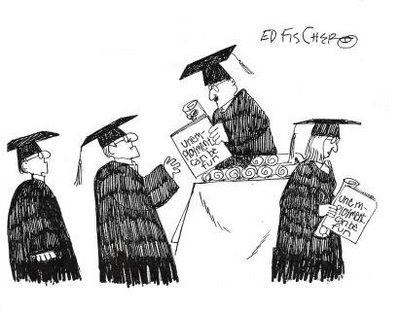Sarinah. Baru-baru ini terjadi ledakan bom bunuh diri di tempat itu, yang pula memakan tujuh orang korban meninggal dunia. Diberi-nama oleh Sukarno, bapak bangsa kita, dengan nama pengasuhnya dulu saat ia masih kanak-kanak. Sarinah. Diharapkan jadi tempat berkumpulnya masyarakat kecil dimana kebutuhan mereka dapat mudah mereka temui (demikian cita-citanya). Sarinah. Bernama sama dengan buku ini.
Siapa yang tak kenal Sukarno sebagai seorang pecinta wanita tersohor (aku tidak tahu pasti berapa jumlah istrinya). Tetapi ia tidak hanya mencintai wanita sebagaimana makna cinta yang dikenal banyak orang (meskipun tentu tak lepas dari itu). Cintanya membuat ia memikirkan “jalan”, memikirkan “lorong”, yang harus ditempuh para wanita untuk kesejahteraan mereka sendiri.
Buku ini, menurutku, menjadi kado Sukarno pada wanita Indonesia, yang kalaulah boleh kubilang mungkin merupakan hal ketiga yang paling dicintainya (setelah Tuhan dan Indonesia itu sendiri).
Buku ini ditulis di bawah cahaya lilin saat umur proklamasi kita masih berumur sekiranya dua setengah tahun. Ia terangkan dan jadikan landasan bahwasanya kondisinya menulis di bawah cahaya lilin adalah seterang-terangnya alasan bahwa masih banyak yang harus diperbuat oleh Bangsa Indonesia meski telah merdeka. Dan di dalam perbuatan-perbuatan-perlu di masa yang akan datang itu, tidak lah dapat berhasil tanpa keterlibatan wanita.
Kondisi wanita pada saat itu, tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh belahan dunia, ialah menjadi kaum tertindas dari laki-laki. Dampak dari kebablasannya patriarkat yang dianut oleh sebagian besar adat-istiadat manusia. Wanita seringkali dinyatakan sebagai, berdasarkan perkataan Prof Havelock Ellis (dikutip dalam buku ini), “suatu belasteran antara seorang dewi dan seorang tolol”. Maka pada sekitaran abad 18 mulailah muncul perlawanan-perlawanan dari kaum wanita ini.
Dipaparkan dalam buku ini, sejarah singkat pergerakan wanita di dunia. Kebanyakan mengambil contoh di Jerman, sebab di sanalah perjuangan wanita sering ditengok pada masa-masa itu. Karena kuatnya landasan pergerakan. Karena kuatnya semangat berjuang.
Terdapat tiga tingkatan pergerakan wanita, merujuk pada buku ini.
Tingkatan pertama ialah pergerakan yang sangat lemah atau bila perlu tidak dinamakan pergerakan. Sukarno bahkan menyebutnya “main putri-putrian”. Pada tingkatan ini, para wanita-wanita ningrat berkumpul dalam suatu klub-klub atau perkumpulan dimana mereka menghabiskan waktu mengusir rasa bosan. Berusaha menyempurnakan diri sebagai perempuan agar ia disukai laki-laki dan tidak direndahkan. “Sama sekali jauh terasing dari massa, dan tidak berisi ideologi sosial dan ideologi politik apapun.”
Kemudian adalah tingkatan kedua, yakni tingkatan yang lebih sadar membantah kelebihan hak kaum laki-laki. Tidak hendak “menyempurnakan” kaum perempuan buat kesempurnaan pengabdian pada kaum laki-laki, tetapi satu tingkatan yang lebih sadar menuntut persamaan hak, persamaan derajat dengan kaum laki-laki, dalam hal menempati lapangan-lapangan pekerjaan dan hak pilih.
Gerakan ini ialah gerakan feminisme. Gerakan ini melihat laki-laki sebagai lawan. Yang kemudian gerakan ini mulai pudar sebab timbulnya kesadaran di kalangan perempuan proletar bahwa penggerak feminisme pada dasarnya adalah perempuan kelas borjuis yang ingin mendapatkan hak yang sama dengan yang dimiliki oleh suami mereka. Maka gerakan ini bukan semata-mata pergerakan yang utuh dari kaum perempuan melainkan perjuangan kelas dari kaum perempuan borjuis.
Kaum perempuan proletar sendiri sudah dapat turut serta dalam kegiatan produksi masyarakat dalam industri-indusri. Namun yang mereka butuhkan lagi adalah pemanusiaan pekerjaan mereka (saat itu mereka ada yang bekerja hingga 12 jam sehari). Bekerja semacam kuda beban seperti itu yang belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah tangga yang menunggu di rumah membuat ada “retak” dalam jiwa mereka.
Maka tidak puaslah kaum perempuan proletar dan lahirlah tingkatan pergerakan perempuan yang ketiga, yakni gerakan perempuan yang tidak hanya menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini menuntut perubahan susunan masyarakat sama sekali. Sebab apalah gunanya persamaan hak saja kalau toh perempuan dan juga laki-laki, kedaa-duanya, sebagai kelas, tertindas.
Gerakan ini kemudian terus berkembang (bersamaan dengan gerakan sosialis) dengan menjadikan hak memilih dan dipilih sebagai tujuan paling dekatnya untuk mencapai tujuan akhirnya yakni suatu susunan masyarakat yang sama sekali baru. Gerakan ini tidak menjadikan laki-laki sebagai musuhnya melainkan berjuang bersamaan dengan laki-laki.
Demikianlah tiga tingkatan pergerakan perempuan menurut Sukarno, sang agitator ulung. Ia berapi-api memaparkan dalam bukunya ini bahwa hanya dalam masyarakat sosialis lah para wanita dapat menemukan kebahagiaannya. Ia memuji-muji tingakatan ketiga dan berharap perempuan Indonesia segera dapat mencapai tingkatan itu.
Terbukanya kesadaran perempuan itu penting terlebih saat itu Bangsa Indonesia tengah membutuhkan seluruh segenap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sukarno mengutip berulang-ulang kata-kata Gandhi, “Banyak sekali pergerakan-pergerakan kita kandas di tengah jalan, oleh karena keadaannya wanita kita…” dan juga kata-kata Lenin, “Jikalau tidak dengan mereka (wanita), kemenangan tak mungkin kita capai.”
Tetapi, “siapa yang dapat menolong wanita jika wanita sendiri tidak memecahkannya? Tidak berusaha, tidak bertindak, tidak beraksi, tidak pula mencari jalan?”
“Hai, wanita-wanita Indonesia, jadilah revolusioner,-tiada kemenangan revolusioner, jika tiada wanita revolusioner, dan tiada wanita revolusioner jika tiada pedoman revolusioner!”
Ah, Perempuan. Sudahlah ada pedoman revolusioner melalui buku ini (saya kira), maka sudahkah Kamu menjadi wanita revolusioner?
Judul Buku : Sarinah
Penulis : Ir. Sukarno
Penerbit : Yayasan Bung Karno bekerjasama dengan Penerbit Media Pressindo
Tahun Terbit : 2014 (cetakan baru, buku ini juga memiliki cetakan lama dengan ejaan lama)