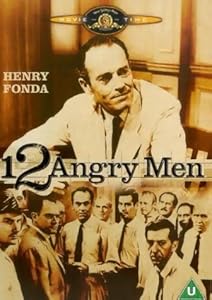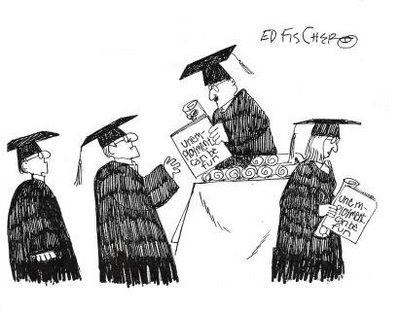Jiwa yang adalah seorang pemuda
pendiam pecinta puisi jatuh cinta pada Nanti yang memiliki senyuman memikat.
Mereka menjadi pasangan kekasih yang begitu saling melengkapi. Nanti selalu
menjadi pembaca pertama karya-karya Jiwa. Jika karyanya bagus maka Jiwa akan
mendapatkan ciuman, jika jelek maka tidak (Nanti mengakui betapa kesalnya ia
jika Jiwa menulis karya jelek). Hal ini lah barangkali yang paling dirindukan
Jiwa, bahwa Nanti selalu menjadi penyemangatnya dalam menulis.
Saya berusaha keras untuk tidak memberikan spoiler lebih jauh. Jadi, kira-kira begitulah apa
yang diceritakan dalam buku tersebut.
Sangat banyak kata-kata
puitis dalam buku ini yang tentu membuat kita tidak bisa melupakan bahwa
seorang Aan Mansyur memang berbasic seorang
penyair.
“tetapi hidup selalu
punya tetapi.”
menjadi kalimat quotable pamungkas dari buku ini, saya
rasa.
Saya menyukai buku ini dari
bagaimana mengalirnya bahasa yang digunakan. Juga betapa cerdasnya Aan memilih
bentuk sebagai “naskah buku yang diterbitkan”. Dengan bentuk yang seperti ini,
kita akan temui banyak sekali catatan kaki yang berisi pikiran Nanti atas suatu
kejadian yang diceritakan Jiwa. Atau sekedar mengatakan bahwa Jiwa terlalu
berlebihan dan sangat subjektif menceritakan apa yang mereka alami berdua. Sehingga
kita akan melihat bahwa sosok yang sebenarnya memainkan peran di sana adalah;
Jiwa si penulis, Nanti versi Jiwa, dan Nanti yang Sebenarnya. Meskipun tentu
saja kita bisa berasumsi bahwa saat Nanti yang Sebenarnya menyangkal apa yang
dilakukan Nanti versi Jiwa pada catatan kaki, Nanti yang Sebenarnya bisa saja
berbohong.
Bagi penggemar Aan, pasti akan
segera sadar mengenai kedekatan karakter Jiwa dengan si penulis itu sendiri.
Bahwa Jiwa diceritakan sebagai pengidap penyakit jantung sebagaimana Aan. Jiwa
yang seorang penyair. Jiwa (yang bersama nanti) membangun Perpustakaan Terakhir
(dalam kehidupan Aan, ia membangun perpustakaan Kata Kerja) .
Ada banyak kemiripan yang membuat
saya sendiri (atau mungkin sebagian besar pembaca) secara sepihak merasa bahwa
buku ini adalah autobiografi dari si penulis. Hal ini menyenangkan mengingat
bahwa saya adalah penggemar Aan, juga sekaligus mengerikan, karena beberapa
bagian dalam buku ini yang tidak terbayangkan jika benar seorang Aan ternyata pernah
melakukannya.
Kemiripan karakter ini, jika
ingin berlaku adil, menurut saya (yang hanya seorang awam) membuat buku ini
belum dapat kita sejajarkan dengan novel-novel lain. Dalam artian bahwa, tentu
seorang pencerita ingin menceritakan sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya
sehingga mampu meyakinkan pembaca, namun bagaimanapun, ini bisa jadi
menunjukkan kemalasan dan kekurangan ide untuk menggali dan mendalami sosok
karakter yang lain yang jauh berbeda dari dirinya sendiri.
Apapun itu, saya melarang keras
para perempuan-perempuan atau pria tipe Susah
Move On untuk membaca buku ini. It’s
a big NO! Kamu bisa baper berkepanjangan. Percayalah!
(tulisan ini pernah dimuat di tulismenulis.com)
(tulisan ini pernah dimuat di tulismenulis.com)
Judul buku :
Lelaki Terakhir yang Menangis di Bumi
Penerbit : Gagas Media
Halaman : 276
Tahun Terbit : 2015
ISBN :
9797808165